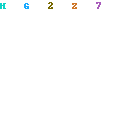Pukul 23.45 WIB. Seorang pemuda berjalan sendiri meninggalkan Bandara Adi Sucipto. Ia baru saja menghabiskan perjalanan udaranya dari tempat yang jauh. Gurat wajahnya tegas, tampak segar dengan bekas air wudhu yang masih membasahi rambutnya. Tak seperti penumpang lain, barang bawaannya terkesan lebih simpel. Sebuah tas ransel menempel dipunggungnya dan koper berukuran sedang dibawah kendali tangan kanannya. Suara merdu operator perempuan baru saja terdengar dari speaker beberapa saat lalu, memberikan sambutan selamat datang bagi para penumpang pesawat yang baru saja landing. Ia telah menyelesaikan perjalanan udaranya dari Negeri Paman Sam setelah transit lebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Berjalan tagap, pemuda itu meninggalkan bandara. Berniat melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Ia memilih menghentikan taksi untuk mengantarnya pulang tanpa terlebih dahulu memberi kabar keluarga di rumah. Mungkin saja ia bermaksud memberi kejutan pada orang-orang di rumah. Meski matanya terasa berat, tiga tahun tak melihat kampung halaman memutuskan dirinya untuk menikmati perjalanan sisi kota yang tak banyak berubah. Suasana Jogja yang tak pernah sepi. Kerlap kerlip hiasan lampu kota tampak temaram memamerkan keindahannya. Di trotoar jalan, anak-anak muda masih banyak berkeliaran merayakan kebebasannya. Sebagian saling bergerombol, tak sedikit dari mereka berdua saja dengan kekasihnya, si lelaki memainkan rambut panjang kekasihnya, berdempet bergandeng tangan. Fenomena yang memuakkan. Tak berbeda dengan orang – orang muda di negeri perantauannya yang belum dua puluh empat jam ia tinggalkan. Negeri Hollywood benar-benar talah menjadi kiblat anak muda jaman sekarang.
Pemuda itu kemudian mengalihkan perhatian ke sudut lain, menatap sekilas beberapa anak muda yang tampak asyik bercengkrama dengan cat semprot warna warni di depan tembok besar yang berdiri kokoh di tepi jalan. Mural atau graffiti, itulah istilah untuk aktivitas yang sedang mereka lakoni. Teknik menggambar di sebuah bidang besar permanen seperti tembok. Graffiti sendiri merupakan bagian dari mural, yang coretan-coretannya cenderung berupa hanya berupa tulisan.
Tiba-tiba ia menyuruh si supir taksi untuk merapat dan memutuskan untuk turun. Ia mengurungkan niat untuk sampai di rumah lebih awal. Pemuda itu kemudian mampir ke sebuah warung lesehan untuk sekedar istirahat dan duduk-duduk sejenak.
“Lele bakar kalih jeruk panas, setunggal nggih bu1.” Katanya ringan sambil mengacungkan telunjuknya. Tiga tahun hidup di negeri orang tak membuatnya lupa dengan bahasa jawa kebanggaannya. Ia bahkan tak melewatkan menu makanan favoritnya ketika kuliah S1 dulu. Usai makan, ia tak kunjung beranjak. Tak jauh beberapa meter di sebrang jalan tampak para pemuda yang tadi sempat menjadi perhatiaanya beberapa saat lalu. Segerombolan anak muda yang asyik berekspresi di depan tembok. Pikirannya tiba-tiba membawanya ke masa lalu, seakan sebuah roll kaset diputar ulang di memorinya kembali ke masa lalu.
*****
Megendap-endap tengah malam, di antara tepi-tepi jalan raya. sesekali aksinya ia lampiaskan dalam gelapnya trowongan atau tembok-tembok jembatan di bawah fly over yang berdiri angkuh. Seangkuh karyanya yang terkadang menjadi gunjingan bagi sebagian orang. Di sisi lain, semprotan cat dan goresan kuas dari tangan lihainya merupakan karya seni luar biasa yang kini menjadi primadona di tengah hiruk pikuk keramaian jalan raya di berbagai kota.
“Lif,,, satu warna terakhir!” Ujar Daud pada kawan disampingnya, seraya mengulurkan tangan meminta cat untuk menyelesaikan graffitinya. Spontan tangannya berayun menangkap cat semprot yang dilempar sang kawan. Alif, sohib setianya yang tak pernah telat menemani setiap kali Daud berhasrat untuk Ngebom, istilah bagi para Bomber, sang seniman graffiti. Sedangkan Alif, terlepas dari sohib setianya, ia tak lebih dari sekedar asisten yang sama sekali tak memiliki bakat yang sama seperti Daud. Sekedar menjadi teman ngobrol dan membantu ini itu ketika Daud tengah asyik menekuri graffitinya.
Srrooott… kini ia telah sampai di semprotan terakhir. Kakinya mundur beberapa langkah, mengamati hasil karya tangan lihainya sembari membandingkan dengan desain di atas secarik kertas yang sudah lusuh. Dibalik kacamata minus empatnya, matanya memicing sambil mengembangkan kedua ujung bibirnya ke atas. Di belakangnya, Alif yang duduk di trotoar seberang jalan membaca karya sang bomber yang baru saja usai. “Aufklarung”. Itulah graffiti hasil karya Daud malam ini. Sebuah ‘pencerahan’ yang tengah ia harapkan hadir dalam kerumitan ujian kehidupannya.
Sang bomber biasanya menuangkan inspirasinya dalam sebuah tulisan tertentu yang memiliki makna tersendiri, yang terkadang makna itu terlalu abstrak hingga tak sembarang orang memahaminya. Tak jarang graffiti menjadi sarana dan bahasa rahasia dengan komunitasnya, atau bahkan berisi ekspresi ketidakpuasan terhadap kondisi sosial. Yang unik bagi Daud dan Alif, pernah suatu kali mereka menuliskan besar-besar nama perempuan yang sempat mereka sukai diam-diam di tembok gerbang belakang sekolah. Pagi harinya, mereka tersenyum puas mendapati kedua perumpuan yang dimaksud terperangah, setengah mati mencari para pelaku yang tak pernah terbongkar hingga kini.
Daud duduk merapati Alif, meneguk secuil air yang tersisa di botol yang sengaja mereka bawa. Aktivitasnya malam ini cukup membuatnya lelah. Buaian dingin angin malam menyeruak, menyeka keringat yang membasahi tubuh ringkihya, melalui pori pori kulitnya hingga menusuk tulang.
“Ayo...!!” keduanya lalu bangkit dan meninggalkan area yang tiga puluh menit lalu menjadi madan kekuasaannya. Berjalan menyusuri pinggiran kota dini hari. Jam di tangan Alif menunjukan tepat pukul dua. Setiap inchi jarak yang mereka lewati menampakan sisi lain kehidupan yang tak semestinya ada. Beberapa gelandangan dan Pengemis tampak tertidur pulas, seakan tak pernah ada beban yang membelenggu kehidupan mereka. Beberapa meter perempatan jalan di depan tampak beberapa waria dan wanita tuna susila tengah menjajakan jasanya. Ada juga segerombolan anak-anak muda tengah asyik dengan genjrengan gitar dan asap rokok yang terus mengepul. Hufh… sepertinya dunia ini tak pernah sepi. Keduanya masih berjalan tanpa arah, bermaksud menghabiskan malam ini di jalanan sepenuhnya, sesekali bercakap-cakap riang mengenang cerita-cerita masa lalu atau tarbahak memimpikan masa depan.
“Kau tahu Lif, aku berjanji, kelak aku akan menjadi seniman besar seperti Affandi dan Basuki Abdullah.” Begitulah Daud berikrar, usai menarik nafas panjang di sela-sela mimpinya yang sedang mereka rangkai. Berharap malaikat menyimpul mimpi-mimpinya dan Tuhan berkenan mengabulkan.
“Tentu saja kawan, kelak aku pun tak mau kalah seperti Habibie yang telah menerbangkan Gatut Kaca nya.” Alif tak kalah menimpali tentang mimpinya, “ atau berkeliling dunia dan menemukan desa Edensor seperti Andrea Hirata dalam novelnya.”
Keduanya terbahak. Setengah tak percaya dengan masing-masing bualannya.
“Bersyukurlah kau masih berkesempatan melanjutkan study mu, kawan. Meski aku tak seberuntung kau, aku yakin Tuhan telah menakdirkan untukku jalan yang tak kalah indah darimu” begitulah akhir obrolan hangat malam itu. Keduanya lalu tersenyum. Kini mereka melangkah masuk ke dalam Mushola kecil di sudut kota. Bersungkur rata dengan tanah, melebur, menyatu dengan segala kerendahan memohon pada Sang Kuasa untuk suatu makna hidup yeng berarti
****
Pagi yang cerah, seminggu berlalu usai Daud ngebom sabtu malam lalu. Ia baru saja terbangun dari ketidurannya usai sholat Subuh tadi. Sajadahnya masih tergelar disudut kamarnya yang mulai terang oleh berkas-berkas sinar matahari yang menembus jendela kaca kamarnya. Sekilas wajah kamarnya mulai terlihat, tampak dinding-dinding kamarnya penuh coret-coret graffiti abstrak buah karyanya. Buku-buku bertumpuk berserakan bercampur pakaian yang tak jelas bersih atau kotor. Lengkap sekali, mulai dari buku-buku sastra favoritnya karya Gibran, Taufik Ismail, Goenawan Muhammad, hingga buku-buku pergerakan. Bahkan beberapa kitab besar seperti Fiqh, Manhaj dan Ihya Ulummudin ikut tertumpuk diantaranya. Rasanya kontras sekali jika dibandingkan dengan kebanyakan seniman yang terkenal semrawud. Liberal dan sekuler, berpikir parsial antara seni dengan religi. Daud bukan demikian. Alamarhum ayahnya mantan pemimpin Pergerakan dan tokoh berpengaruh dimasyarakatnya. Sisi dirinnya yang demikian tak lain didikan ayahnya.
Daud terpaksa mengalah pada nasib. Keinginannya untuk melanjutkan study harus lenyap. Emaknya hanya bakul sayur di pasar Demangan. Jangankan untuk biaya kuliah, emaknya bahkan harus banting tulang sendiri untuk kebutuhan Daud dan keenam adiknya. Sayang sekali prestasi akademiknya tak begitu menonjol, sehingga Beasiswa yang ia usahakan belum mampu ia tembus. Usai lulus Sekolah menengah kemarin, hari-harinya hanya membantu Emak jualan di pasar. setelah itu, bebaslah ia menuangkan ekspresinya. Sesekali berkutat dengan cat di depan kanvas, menari kan pena diatas kertas, bahkan genjrengan dengan kort dan gitar rombengnya yang hanya tinggal lima senar.
“Daud, koe iki opo ora mesake emak. gek nyambut gawe. Adi-adimu kuwi isih cilik-cilik to le…2” pagi itu, emaknya nyletuk ketika Daud menemani berjaga di pasar. Daud hanya menjawabnyanya enteng
“ Enggih mak, sesuk Daud golet gawe3” kemudian ia minta izin ke Mushola di sudut pasar untuk menunaikan Dhuha. Meski ia tampak acuh dengan ucapan Emak baru saja. Berat benar hatinya akan tanggung jawab yang ia lalaikan sebagai sulung. Terlebih dirinya sebagai laki-laki dan ayahnya yang telah almarhum.
Sore itu, dihari yang sama. Ketika Daud tengah terluntang-lantung tak jelas dengan sepeda ontelnya di Kawasan Malioboro, ia bertemu kang Epi. Rekannya yang juga hobi di bidang seni. Keduanya lalu mampir di sebuah angkringan di sudut Alun-alun, ngobrol dan diskusi tentang banyak hal.
“Ah ya, lama aku tak bisa menghubungimu. Aku bahkan lupa untuk memberitahu. Lukisanmu yang kau titipkan bulan lalu sudah ada yang ngambil. Mantap boi, tiga ratus ribu. Tak main-main kau memberi harga untuk lukisan abstrak ngawurmu.” Kang Epi menyeringai, ia sodorkan tiga lembar uang berwarna merah jambu pada Daud.
Daud kaget tak percaya. Ia bahkan sekedar iseng saja menitipkan lukisannya di galery milik rekan kang Epi. Matanya berbinar menerima uang dari hasil karyanya. Terharu. Bayangan Emak dan adik-adiknya sekejap terlintas. Mereka pasti senang dengan berita ini. Pucuk dicinta Ulam pun tiba. Bukan suatu kebetulan, Kang Epi bahkan memberi tawaran kepada Daud untuk bekerja di galery milik kawannya itu.
“Yang bener aja kang, itu kan galery terkenal. Pengunjung dan pembelinya aja kebanyakan turis asing yang berani bayar mahal lukisan-lukisannnya. Lah wong lukisanku aja semrawut kok. Mana ada yang mau nglirik.” Ujar Daud masih tak percaya
“Lah itu apa namanya kalo bukan dilirik. Serius boi, aku bahkan tak meragukan karyamu. Toh upah bulanannya lumayan. Apalagi kalo lukisanmu laku.” Kata Kang Epi lagi.
“hmmm.. beres deh kang.” Senyumnya mengembang, dengan senang hati Daud menerima tawaran Kang Epi. rasa syukurnya ia tumpuhkan dalam doa usai menunaikan Sholat Maghrib di Masjid Gedhe Kraton. Ia langsung menarik ontelnya menuju rumah Alif sahabatnya.
“Aku punya kejutan kawan.” Daud melempar tubuhnya ke kursi, “bayangkan, lukisanku yang kutitipkan di galery milik rekan kang Epi laku terjual. Aku bahkan dapat tawaran untuk bekerja di galery nya.” Ujar Daud girang “besok akan ku kabari kejutan ini pada emak dan adik-adik. Ternyata aku bisa membuktikan bukan, kalo karyaku memang tak sia-sia.” Ujarnya menggebu
“Aku turut bahagia, kawan” kata Alif ikut tersenyum
“Sepertinya akan semakin seru kalo malam ini kita ngebom lagi. Ayolah, kita rayakan ini.” Seperti biasa sang Bomber satu ini selalu berhasrat untuk bermain dengan perangkat catnya di setiap momentum yang membuat hidupnya berkesan
Keduanya lalu keluar tengah malam, sekitar pukul 23.40. mengendap-endap mencari tempat yang tepat untuk lahan graffitinya. Seperti biasa, Daud mampu menaklukan sendiri tembok di depannya dengan cat di genggaman tangan lihainya. Sesekali Alif memberi masukan tentang graffiitinya kali ini. Tak banyak waktu yang Daud butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Enam puluh menit berlalu. Graffitinya telah mampu terbaca. ‘Greatest Allah’. Begitulah, sebuah ungkapan syukur luar biasa untuk Rabb yang telah memberi nikmat tak terbatas
Dalam perjalanan Pulang, Daud merasa tak tenang. Sesuatu yang aneh tampak menyelimuti mereka berdua. Seperti ada yang tengah mengikutinya di belakang. Daud menoleh, tak ada siapapun. Keduanya lalu melanjutkan jalannya di trotoar. Jarum di jam tangan Alif menunjukan pukul 01.38 dini hari. Posisi mereka kini berada di sekitar kelurahan Kotabaru. Tidak jauh darinya perkampungan di sekitar bantaran Kalicode tampak padat dan kumuh. Masih banyak orang – orang berkerumun disana. Tak sedikit pasangan lelaki dan perempuan masih bersembunyi dibalik keremangan. Sebuah motor melintas kencang. suaranya yang nyarig di tengah kesenyapan malam memekakan telinga keduanya. Perasaan Daud semakin tak tenang. Dari sejak di Jalan Mataram tadi masih saja seperti ada yang mengikutinya. Lima menit berlalu, keduanya masih melanjutkan berjalan. Motor yang sama melintasinya lagi. Kali ini tak secepat sebelumnya. Seorang pengendara berjaket hitam dengan kepalanya tertutup helm rapat. Dibelakangnya seorang penumpang mengenakan kaos lengan panjang dan jin belel menatap tak enak pada Daud. Matanya memicing, wajahnya seakan menyimpan dendam pada orang yang ditatapnya. Daud semakin panik, ia bahkan tak mengenal sama sekali kedua lelaki itu. Sedangkan Alif sama sekali tak menyadari keanehan yang mengejar Daud sedari tadi.
“Lif, sepertinya kita harus segera pulang.” Daud berjalan kian cepat, yang dituju adalah Masjid Syuhada, dimana ia memarkirkan sepeda ontelnya malam tadi. Belum sampat sampai tujuan, untuk ketiga kalinya motor yang sama melintasinya, kali ini dua motor yang lain mengikutinya dibelakang. Masing-masing membawa seseorang yang momboncengnya di belakang. Ketiga motor tersebut tempak melambat mendekati mereka berdua. Tiba-tiba tiga orang boncengannya melompat dari motor mengelilingi Daud dan Alif. Keduanya benar - benar panik, belum sempat mengadakan percakapan, seorang diantaranya memberikan bogeman keras tepat di muka Daud, menjadikan beberapa pembuluh darahnya sobek, seketika darah segar mengalir dari hidung dan ujung bibir Daud,
“Sialan! Siapa Kalian Hah?!” Daud berteriak, setengah berlari ia membalas bogeman si preman, tepat mengenai sasaran yang sama. Tak jauh darinya Alif tengah di kroyok tiga preman lain yang tak dikenalnya. Masing masing satu melawan tiga. Pertarungan sudah semakin tak bisa dihindarkan. Enam lelaki tak dikenalnya tersebut membabi buta mengroyok Daud dan Alif, tak ada percakapan sedikitpun. Para mulut preman tersebut hanya bungkam disambing tangannya yang terus menghajar.
Bughhh…
Untuk kesekian kalinya bogeman keras mendarat di perut Daud ketika ia hendak mengeluarkan kalimat. Sepuluh menit berlalu, tak ada tanda – tanda para preman tersebut akan berhenti mendaratkan pukulannya. Tak seorangpun lewat di tempat ini untuk dimintai tolong. Keduanya sudah tak berdaya. Darah merah segar mengalir di setiap bagian tubuh mereka, wajahnya bahkan sudah tak berbentuk lagi. Daud sudah terlebih dulu ambruk ketika entah pukulan yang keberapa mendarat tepat di ulu hatinya. Terasa sekali pukulannya telah mengenai organ dalamnya hinga ia tak lagi sedarkan diri. Badannya terpental dengan darah termuntahkan dari mulutnya. Tak lama setelahnya beberapa warga ada yang melihatnya, mereka segera berlari hendak menolongnya. Baru saat itulah preman-preman tersebut mundur. Memilih menstater motornya dan terbirit manjauh segera. Sayang sekali warga tak sempat membekuknya.
Kali ini Daud dan Alif lah yang harus segera mendapat pertolongan. Alif masih setengah sadar ketika warga menolongnya. Ia melihat Daud tergeletak di jalan dengan darah melumuri tubuhnya. Ia bahkan tak tahu, kawannya telah menghembuskan nafas terakhirnya ketika warga belum sempat menolongnya.
Sekejap, dunia menjadi kelam.
*****
Seketika lamunan pemuda di warung lesehan itu buyar. Seakan roll kaset yang sedang di putar di memorinya rusak dan tak mampu lagi melanjutkan film yang terekam di dalammnya. Butiran-butiran bening menetes di pipinya. Matanya telah basah sembari menatap gerombolan bomber di sebrang jalan yang tengah asyik ngebom dengan graffitinya. Membawanya pada kenangan-kenangan masa lalu bersama si bomber sahabatnya, Daud. Ketika mereka berdua berjalan – jalan mengitari kota Jogja hampir tiap malam. Ketika dirinya hanya duduk-duduk membaca buku pelajaran di belakang sedangkan di depannya daud tengah asyik berkutat dengan graffitinya. Ketika Daud dengan amat bangga atas kejutan yang hendak ia sampaikan pada emak dan adik-adiknya. Ketika Daud membuat garafity terakhirnya bertuliskan ‘ Greatest Allah ’ dan juga tentang akhir dari kejadian itu. Ketika tenyata ia benar-benar talah pergi
Malam ini, Alif benar-benar urung untuk pulang. Berniat menghabiskan malamnya di atas Sajadah masjid kota. Dan berjumpa dengan makam sahabatnya lebih dulu. Allahummaghfirlahu…
1Lele bakar sama jeruk, satu bu.
2Daud, kamu ini apa tidak kasihan sama ibumu. Sana cari kerja. Adik-adikmu itu masih kecil-kecil, Le(Panggilan untuk anak laki-laki di Jawa)
3Iya bu, besok Daud cari kerja